Well, we're at the end of March 2020. Jangan tanya kemana saja gue karena gue juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba sudah bulan Maret 2020 dan tidak begitu paham apa saja kegiatan yang gue lakukan dari terakhir kali menulis blog hingga detik ini gue bisa posting lagi. Yang jelas, di tahun baru kemarin salah satu resolusi gue adalah untuk menulis lebih banyak dan ide yang lebih produktif, namun sayangnya hingga bulan ketiga di tahun ini, tidak ada yang terwujud dan otak bersamaan dengan jari gue begitu malas menulis.
I
had so many updates in life, so many things coming and gone, and so many
emotions felt, yet sometime I still feel empty inside –
but blah, that is okay. First thing first, I finally came to decision to leave
my hometown, and got myself a place in Kabupaten Bandung, dikelilingi
pegunungan dan udara dingin, sesuai naturku pada biasanya. Second thing, I am
still a doctor and now I am placed (just like all of you) IN THE MIDDLE OF A
PANDEMIC. COVID-19 is making us all crazy and also, inhumane at some points.
Supermarket all clear dari barang-barang, terutama tissue, hand-sanitizer, masker, dan
sabun, orang-orang self-quarantined dan work from
home, perusahaan tidak beroperasi, Rupiah anjlok, dan
gue masih di sini, di rumah sakit, dengan pasien yang nambah banyak dengan
proporsi yang sakit 'biasa' lebih banyak dari pada yang benar-benar membutuhkan
pertolongan unit gawat darurat. Sakit 'biasa' secara definisi adalah keluhan seperti sakit gigi dimana pasiennya masih bisa ngobrol dan senyum-senyum, BAB 3x sehari cair sejak 4 jam sebelum ke RS, atau demam sejak 2 jam lalu, dimana pasiennya udah berobat ke klinik 1 jam yang lalu tapi merasa belum membaik, karena obatnya belum diminum. Sungguh, di era pandemi yang virusnya udah mulai disinyalir ditransmisikan lewat udara (airborne) – bukannya droplet lagi, keputusan untuk pergi ke UGD/RS untuk sakit yang sebenernya bisa beli obat sendiri adalah membahayakan diri sendiri.
Hey, mengeluh di intro adalah jalan ninjaku.
So let's just jump from me whining, jadi gue udah ngasih hint di post sebelumnya bahwa ada tempat yang gue kunjungi di 6-8 bulan terakhir. To recall back, I will just attach the photo.
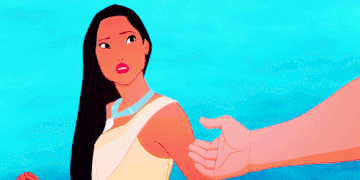 | |
| It's amazing and also frustrating; how this pandemic changed us. |
 |
| I got this GIF here: Greenpeace USA |
Hey, mengeluh di intro adalah jalan ninjaku.
So let's just jump from me whining, jadi gue udah ngasih hint di post sebelumnya bahwa ada tempat yang gue kunjungi di 6-8 bulan terakhir. To recall back, I will just attach the photo.
Simply
judging, gambar ini mengandung unsur perbukitan dengan tone warna cokelat,
dengan gue memunggungi kamera, memakai baju hitam bertuliskan "Bima"
– sebuah kota di Nusa Tenggara Barat yang gue kunjungi di bulan Maret 2019.
Tapi sayang sekali, I would love to get back
there, but the picture itself wasn't taken there.
Jadi, di bulan Agustus kemarin, gue akhirnya naik gunung lagi. Been in love with (simple, non-advanced, recreational) mountaineering since last year and I could not stop thinking about mountain every time it's sunny and specifically, summer. Gue menargetkan sejak tahun lalu, setiap tahun setidaknya naik gunung 2 kali di musim kemarau dan tahun ini di bulan Maret, gue naik ke Tambora walau hanya sedikit dan nggak muncak, dan Agustus ini gue impulsif berdua sama temen ikut open trip lagi. Sempet bingung mau pilih gunung apa untuk didaki karena 1) Mau gunung yang beginner-friendy, karena temen gue baru pertama kali mendaki, 2) … Tapi bukan Papandayan, 3) Maunya tipe gunung yang panas, bukan hutan hujan (contoh: Pangrango). Setelah berkali-kali mikir, apakah mau ke Gunung Gede, Semeru sampe Kalimati saja, atau Papandayan (lagi), pilihan jatuh kepada Gunung Prau.
Jadi, di bulan Agustus kemarin, gue akhirnya naik gunung lagi. Been in love with (simple, non-advanced, recreational) mountaineering since last year and I could not stop thinking about mountain every time it's sunny and specifically, summer. Gue menargetkan sejak tahun lalu, setiap tahun setidaknya naik gunung 2 kali di musim kemarau dan tahun ini di bulan Maret, gue naik ke Tambora walau hanya sedikit dan nggak muncak, dan Agustus ini gue impulsif berdua sama temen ikut open trip lagi. Sempet bingung mau pilih gunung apa untuk didaki karena 1) Mau gunung yang beginner-friendy, karena temen gue baru pertama kali mendaki, 2) … Tapi bukan Papandayan, 3) Maunya tipe gunung yang panas, bukan hutan hujan (contoh: Pangrango). Setelah berkali-kali mikir, apakah mau ke Gunung Gede, Semeru sampe Kalimati saja, atau Papandayan (lagi), pilihan jatuh kepada Gunung Prau.
Gunung
Prau secara administratif terletak di 3 Kabupaten: Kabupaten Batang, Kabupaten
Kendal, dan Kabupaten Wonosobo, tapi paling sering digapai lewat Wonosobo,
karena termasuk dalam gugusan Dataran Tinggi Dieng dan masih banyak atraksi
lain di sekitarnya, misal Telaga Warna, Kawah Sikidang, dan lain-lain. Gunung
Prau diklaim sebagai beginner-friendly sampai-sampai pintu masuk pendakiannya penuh dengan
rumah persinggahan, dan puncaknya bisa penuh dengan kemah di masa liburan. Kata
orang, Prau gunung yang menyenangkan dan tidak terlalu tinggi, 2565 mdpl saja.
Akhirnya tanpa banyak babibu dan langsung setuju, gue dan teman gue kali ini,
Clarissa, bergabung lagi bersama strangers di sebuah meeting point di Jakarta
Selatan. Rasanya senang sekaligus thrilled
salam-salaman lagi dan kenalan lagi sama orang baru lewat open trip. Kebanyakan teman-teman usianya
sebaya kita tapi pergi berpasangan cewek-cowok. Cuma gue dan Clarissa yang
pergi berdua cewek-cewek. Sisanya join open
trip pure sendirian.
Perjalanan dari Jakarta ke Wonosobo memakan waktu sekitar 7-8 jam lewat jalan tol Cipali. Tidak terlalu ingat detil malam itu karena jalanan gelap ditambah jiwa karung beras yang membuat gue bahkan bisa tidur walaupun ada di situasi yang seharusnya tidak bisa tidur. Waktu matahari terbit yang jelas kita sudah ada di Dataran Tinggi Dieng, turun sebentar untuk beli gorengan dan menatap matahari terbit, dan jam 7 kami sudah sampai di Gerbang Patak Banteng. Benar rupanya, Gerbang Patak Banteng merupakan pemukiman padat penduduk yang kebanyakan sudah menjelma tempat pemandian, homestay, atau warung bagi para pendaki.
 |
| Kalo ditanya kenapa mau ke Prau, mungkin karena review beginner-friendly, bisa liat banyak gunung, dan banyak bunga daisy. Source: Pinterest |
Perjalanan dari Jakarta ke Wonosobo memakan waktu sekitar 7-8 jam lewat jalan tol Cipali. Tidak terlalu ingat detil malam itu karena jalanan gelap ditambah jiwa karung beras yang membuat gue bahkan bisa tidur walaupun ada di situasi yang seharusnya tidak bisa tidur. Waktu matahari terbit yang jelas kita sudah ada di Dataran Tinggi Dieng, turun sebentar untuk beli gorengan dan menatap matahari terbit, dan jam 7 kami sudah sampai di Gerbang Patak Banteng. Benar rupanya, Gerbang Patak Banteng merupakan pemukiman padat penduduk yang kebanyakan sudah menjelma tempat pemandian, homestay, atau warung bagi para pendaki.
Setelah
bebersih dan sarapan, pendakian start jam 10 pagi. Sungguh, pendakian
(rekreasional) tersiang selama sejarah gue mendaki. Katanya, untuk mencapai
2565 mdpl tidak terlalu menyakitkan dan hanya makan waktu 3-4 jam, jadi
mulainya bisa dari siang karena pasti pas sore udah sampai di puncak. Gue
ngangguk-ngangguk aja denger pimpinan rombongan bilang gitu, "Oh mungkin
pendakian ini tidak akan terlalu menyakitkan ya, syukurlah. Gue gak terlalu
banyak olahraga sebelum naik ke sini". Yap, salah satu alasan kenapa gue
pilih Prau adalah karena beberapa bulan ke belakang gue jarang sekali olahraga
dan cenderung sedentary lifestyle – ke
tempat kerja pagi-pagi naik motor, kerja dari jam 8 sampe jam 8, kadang bisa
tidur siang dan ngemil banyak di tempat kerja, pulang jam 8 malam kemudian
bablas mampir Warmindo untuk makan indomie rebus pakai telor dan sayuran,
minumnya teh manis. Rutinitas itu berulang selama 1 bulan ke belakang dan
sekarang gue berusaha kembali menekuni hobi yang membutuhkan kapasitas fisik
yang bagus. Mon maap???
Pendakian
dibuka dengan pemandangan sawah ber-terasering. Bersusun dengan indah
mengelilingi daerah pemukiman warga. Sawah terlihat kuning kecoklatan karena
musim kemarau panjang, tapi tetep cantik bukan main. Sampai di gerbang
pendakian, gue langsung lemes liat tangga bersusun sedemikian banyaknya
berwarna-warni. Gue suka warnanya tapi nggak suka dengan objeknya, yakni
tangga. Aku dan tangga dalam pendakian sungguhlah bukan teman baik – tiba-tiba
pikiran gue terbang ke satu tahun yang lalu, waktu gue jatuh di tangga
Pangrango yang banyaknya bukan main, meninggalkan bekas kuku cantengan yang
seminggu kemudian membentuk abses dan gue terpaksa insisi (beset) sendiri di
kamar kos di Serang buat keluarin nanahnya. Tangga bersusun berundak-undak, mau
nggak mau kita naikin satu-satu. Di sinilah kejompoanku (dan jiwa pemalas
olahraga) mulai terkuak, baru naik tangga 5-6 udah melipir karena engap. Naik
lagi, melipir lagi. Begitu terus sampai akhirnya ketemu trek tanah berdebu yang
licin (kering aja licin, gimana basahnya?)
Prau dari permulaan trek sudah nampak seperti gunung untuk turis – baru beberapa langkah melewati
gerbang start pendakian, udah ada yang jual souvenir badge, enamel, dan
lain-lain khas gunung Prau. Mendaki lebih ke atas lagi, ketemu beberapa warung
di kanan kiri jalan menjajakan gorengan dan semangka (sumpah, semangka di
gunung is the best idea human could invent). Tidak jarang warung jualan makanan
besar, seperti pecel ayam dsb. Prau adalah gunung yang ramah dan ceria. Bahkan
warung-warungnya punya background yang
spektakuler – warung nangkring di ujung tebing, dihiasi dengan pemandangan
sawah-sawah yang kecoklatan karena kemarau panjang, serta keliatan gunung lain
dong dari kejauhan (yes, Prau is surrounded by Sindoro and Sumbing – you could catch their silhouettes from Prau).
Semakin atas, trek berubah semakin berdebu dan curam. Trek menjadi tanah dan akar dengan sedikit susunan bebatuan. Di musim kemarau Prau penuh dengan tanah berdebu dan bisa sekali menjadi masker jika kita tidak megenakan penutup wajah. Pendakian pertama gue di Papandayan, sama sekali nggak butuh buff karena tanah Papandayan sama sekali nggak ngepul. Pendakian kedua di Pangrango, butuh buff supaya pipi nggak kedinginan, tapi basically Pangrango adalah hutan hujan tropis yang basah dan lembab. Pendakian ketiga ke Tambora, tanahnya becek karena sedang musim hujan, jadi nggak perlu buff. Cuma ke Prau ini aja butuh banget buff karena berdebu pisan.
 |
| Di Prau, lo bisa melipir setiap 300 meter untuk menikmati makanan warung. Fancy eh? |
Semakin atas, trek berubah semakin berdebu dan curam. Trek menjadi tanah dan akar dengan sedikit susunan bebatuan. Di musim kemarau Prau penuh dengan tanah berdebu dan bisa sekali menjadi masker jika kita tidak megenakan penutup wajah. Pendakian pertama gue di Papandayan, sama sekali nggak butuh buff karena tanah Papandayan sama sekali nggak ngepul. Pendakian kedua di Pangrango, butuh buff supaya pipi nggak kedinginan, tapi basically Pangrango adalah hutan hujan tropis yang basah dan lembab. Pendakian ketiga ke Tambora, tanahnya becek karena sedang musim hujan, jadi nggak perlu buff. Cuma ke Prau ini aja butuh banget buff karena berdebu pisan.
Lebih naik lagi ke atas, trek semakin berundak dengan akar dan tanah, namun berundaknya ini tinggi-tinggi, sehingga kita tidak jarang kita harus menggunakan tangan juga untuk bisa naik (atau mungkin karena gue aja yang pendek). Oleh karena itu sangat dibutuhkan sarung tangan. Kebayang, narik-narik akar sambil berusaha membopong diri yang bawa carrier itu nggak enak, bisa-bisa pas pulang tangan luka-luka dan kapalan. Bukannya soal estetika, tapi ini perihal kenyamanan saat mendaki dan bagaimana kita bisa tetep in-shape sepulang dari pendakian. 3 jam pendakian, kita bisa menemukan kanan kiri trek curam dan bisa melihat beberapa atraksi wisata Dieng dari atas, misalnya Telaga Warna. Kita juga bisa lihat jalan-jalan dan mobil yang berkendara, semua semakin mengecil semakin kita mendekati puncak.
 |
| Diambil dari kejauhan: Telaga Warna. |
Prau,
seperti Papandayan, tidak memiliki puncak definitif, tidak ada titik
tertingginya – dengan kata lain, 2565 mdpl bukan puncak definitif. 'Basecamp
puncak' Prau luas dan datar, dengan hamparan rumput luas dan bunga-bunga liar
yang cantik di beberapa sudutnya. Tapi ada juga sudut yang bertanah – jadi,
pintar-pintarlah memilih lapak berkemah. Pendakian dari pintu gerbang hingga
sampai ke Puncak buat gue memakan waktu 4 jam, dengan stamina orang yang gaya
hidupnya hanya kerja dan rebahan. Kalo lo lebih atletik, bisa lebih gercep lagi
sampe di basecamp teratas pendakian via Patak Banteng ini. Waktu itu, gue tiba
pukul 2 siang, awan masih menggantung, menghalangi pemandangan gunung-gunung
lain (Sindoro, Sumbing, Slamet) yang seharusnya bisa dilihat dari Prau.
Selain pemandangan gunung-gunung di sekitarnya, Prau juga diberkahi kenampakan bukit-bukit – nama familiarnya adalah Bukit Teletubbies. Bukit Teletubbies Prau ini agak mirip-mirip dengan bukit-bukit di Nusa Tenggara Timur (yang namanya juga Bukit Teletubbies), apalagi ketika musim kemarau panjang dan rumput-rumputnya jadi cokelat karena kering. Pertanyaannya adalah, kenapa di negara kita banyak banget yang menamai wilayah perbukitan dengan Bukit Telettubies? Sejujurnya tidak mengerti kenapa semuanya harus Teletubbies – apakah karena tidak ada acara TV lain yang menampakan bukit se-spesifik acara TV Teletubbies?
As expected dari mendaki di kala weekend, puncak Patak Banteng ramai sekali dengan pengunjung, untungnya kita dapet tempat yang cukup datar dan nyaman untuk mendirikan tenda. Setelah beres-beres, kita sibuk mengamati awan yang naik turun menutupi pemandangan gunung-gunung di sekitar Prau. Ditungguin-pun, awan-awan masih senang menghalangi gunung Slamet, Sindoro, dan Sumbing jadi kita memutuskan untuk nyari pemandangan lain aja.
Selain pemandangan gunung-gunung di sekitarnya, Prau juga diberkahi kenampakan bukit-bukit – nama familiarnya adalah Bukit Teletubbies. Bukit Teletubbies Prau ini agak mirip-mirip dengan bukit-bukit di Nusa Tenggara Timur (yang namanya juga Bukit Teletubbies), apalagi ketika musim kemarau panjang dan rumput-rumputnya jadi cokelat karena kering. Pertanyaannya adalah, kenapa di negara kita banyak banget yang menamai wilayah perbukitan dengan Bukit Telettubies? Sejujurnya tidak mengerti kenapa semuanya harus Teletubbies – apakah karena tidak ada acara TV lain yang menampakan bukit se-spesifik acara TV Teletubbies?
As expected dari mendaki di kala weekend, puncak Patak Banteng ramai sekali dengan pengunjung, untungnya kita dapet tempat yang cukup datar dan nyaman untuk mendirikan tenda. Setelah beres-beres, kita sibuk mengamati awan yang naik turun menutupi pemandangan gunung-gunung di sekitar Prau. Ditungguin-pun, awan-awan masih senang menghalangi gunung Slamet, Sindoro, dan Sumbing jadi kita memutuskan untuk nyari pemandangan lain aja.
Tidak banyak hal untuk dikenang setelah matahari terbenam. Prau dingin, sama seperti gunung lainnya yang setidaknya pernah gue jajaki, tapi tidak lebih dingin dibanding pendakian pertama gue ke Papandayan. Malam itu, bintang tidak terlalu banyak tapi ada beberapa, bulan sabit bertengger di langit, orang-orang lalu lalang karena kondisi camp yang ramai. Yang selalu terasa spesial dari malam di atas gunung adalah kopi dan mie instan hangat, sensasi menggesekan kedua tangan dan meniup udara hangat dari mulut untuk mencari kehangatan, dan obrolan-obrolan yang membawa strangers menjadi friends – bahkan family. I don't know which part taking me back again and again to mountains; is it the adventure and adrenaline rush? Is it the peace and serenity? Is it the coffee? Or is it the new friends? Tapi, pemikiran-pemikiran kenapa dan karena itu selalu hilang sudah di atas gunung – yang ada hanya "Oh sekarang gue di sini dan rasanya selalu sama: Enak, nyaman, seperti pulang ke rumah."
Pagi hari pukul 5, teman gue sudah ribut kasak kusuk di sekitar tenda, sementara gue masih bergeliat malas di dalam sleeping bag yang didobel lagi dengan emergency blanket karena suhu semalam mendadak super dingin, gigi temen gue mulai gemeretakan, dan entah kenapa di sebelah tenda gue yang tadinya lahan kosong jadi terisi dan penghuni tendanya super gaduh, terdiri dari suara 4 orang ketawa-ketawa dan teriak di jam 2 pagi. "Dina, ayo bangun udah mau sunrise". Setelah mengumpulkan nyawa, gue menyeduh kopi di luar tenda (kopi adalah menu wajib pendakian yang artinya jika 2 hari mendaki, minimal 3x ngopi di atas gunung) dan akhirnya menyusul teman gue yang sudah ada di ujung bukit sana asyik memperhatikan awan-awan yang mulai berbaik hati mengalah agar pendaki bisa mendapat sunrise yang layak dengan latar 3 gunung sekitar Prau.
Akhirnya,
awan benar-benar mengalah pada pendaki.
Selamat
pagi, dari Patak Banteng, Prau.
 |
| Ritual ngopi di gunung adalah salah satu motivasi saya mendaki. |
 |
| Dina yang tidak pernah estetik: "Dandanan mamang villa adalah jalan ninjaku" |
 |
| Lautan awan. |
Setelah kenyang menikmati sunrise dengan tiga gunung dan lautan awan (serta sibuk menilai betapa orang-orang lain niat banget ya bawa-bawa bendera Indonesia, bawa baju lucu, kain-kain etnik, dan pernak-pernik lainnya demi dokumentasi yang paripurna), akhirnya kita packing pulang. Perjalanan pulang selalu terasa lebih menyakitkan daripada berangkat (tentu saja! Walau udah berkali-kali naik gunung, setiap turun gunung pasti selalu ada rasa ngedumel 'Kenapa sih gue mau naik gunung lagi dan lagi?'), ditambah dengan lautan manusia yang mau turun dan mau naik, serta medan berpasir. Baru pertama kali ngeliat trek pendakian macet seperti itu, terutama di bagian yang bertangga, dan begitu ketemu medan berpasir, kita kepleset dan meluncur sana-sini – bikin kaki sakit, pantat tepos, dan pasir masuk semua ke dalam baju. Walaupun menyakitkan, tapi kita tiba di rumah singgah 3 jam setelah turun dari camp dan akhirnya mandi untuk mengusir pasir-pasir yang nempel di badan akibat siklus bangkit-kepleset-bangkit-kepleset. Jangan kira kita riang sentosa dan mandi lancar jaya – masih tetep ramai, mandipun harus antre dan pinter-pinter cari rumah yang kamar mandinya lagi kosong.
 |
| Anggep aja ini foto real yang nggak pake effort cari spot: Emang sepenuh itu basecamp-nya. |
 |
| Nah ini foto yang lebih effort cari spot supaya nggak kehalangan orang (alias review tipu). |
Ya, naik gunung hits memang ada suka dukanya deh, gue akui.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jadi, setelah ke riweuhan mencari air mandi (padahal biasanya gue cuek sih nggak pernah mikirin mandi, mandinya pas balik ke rumah), akhirnya kita cabut dari Dieng pukul 1 siang – menelusuri lekuk tubuhnya yang molek dengan full musik dangdut koplo in the house. Sampai di sekitar daerah Pancoran Jakarta pukul 2 pagi dan sampai di Tangerang pukul 3 pagi – dan jam 8 pagi gue kerja seperti biasa dengan kedua tungkai yang super sakit walaupun selama pendakian dibantu sama trekking pole. Intinya, tidak ada gunung bagi pemula – semua butuh preconditioning dan stamina. Semua butuh prior research, bahkan beberapa gunung butuh experience. Here are lessons learned from Gunung Prau versi gue:
- Naik gunung itu selalu bawa masker/buff karena bisa saja musim kemarau membuat medan menjadi sangat berpasir dan berdebu. Gak asik kalo pulang dari gunung tiba-tiba sesek napas terus bronkitis. Kalaupun gunungnya gak berpasir/berdebu, masker atau buff bisa buat melindungi wajah dan syaraf-syarafnya dari rasa dingin, sehingga chance untuk lumpuh syaraf wajah (Bell's Palsy) bisa berkurang. Gak lucu juga kalo balik-balik dari gunung muka mencong sebelah karena syaraf wajahnya lumpuh gara-gara kedinginan.
- Trekking pole is no joke – menurut gue wajib kudu harus mesti. Trekking pole mengurangi beban sendi lutut, membuat pembagian berat tubuh menjadi lebih efektif, sehingga mendaki bisa dilakukan dengan lebih ergonomis. Dengan trekking pole, risiko cedera lebih kecil dan juga risiko untuk menderita DS alias dengkul soak pasca mendaki menjadi lebih kecil. Halo, sendi yang lebih happy.
- Naik gunung yang diklaim 'mudah' dan 'hits' memang memiliki suka dukanya sendiri. Sukanya, mungkin medannya tidak terlalu menanjak atau licin, sehingga bisa terjangkau oleh semuanya. Dukanya, tentu saja ramai dan bisingnya yang bikin pusing. Pusing nyari tempat bertenda, pusing karena macet di trek, pusing rebutan WC, pusing cari spot dokumentasi, pokoknya harus udah siap lah kalo ke gunung-gunung hits macem Prau kayak gini. It’s really better to go Prau in weekdays, mengingat kalo weekend banyak yang libur dan memadati gunung – coba deh pergi ke Prau pas hari kerja. Mungkin crowd-nya akan sedikit lebih baik.
- Selalu prior research, baik itu medan, pilihan trek, termasuk do's dan don't's. Mendaki via Patak Banteng memang pilihan utama pendaki, tapi bukan berarti tidak ada trek lain. Titik tertinggi Prau juga bisa dicapai lewat jalur Dieng, namun ternyata lewat jalur Dieng berarti harus melalui luggage checking dan tidak boleh bawa botol plastik! Selalu riset ya, mana kira-kira jalur yang enak untuk rombonganmu dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa dan dilakukan saat pendakian – supaya semua selamat dan senang!
 |
| Dipilih, dipilih lapak kemahnya! |
 |
| Nah contohlah pendaki ini, dia jalan lebih jauh buat cari spot kemah walau di pinggir jurang. |
It's really sweet to finally finish this post after a while.
Semoga manajemen waktu dan keuletan menulis gue cepat sembuh, dan gue bisa naik gunung lagi menyongsong musim kemarau di tahun 2020 ini – karena gue sudah punya bucket list 2 gunung yang mau gue daki di tahun 2020 ini (walau nggak ngerti juga gimana merealisasikannya karena sekarang udah kerja dan jatah cuti sangat limited – dan harus mikirin kesejahteraan rekan kerja juga kalo mau ambil day-off lama-lama – duh, akhirnya omongan gue kayak orang dewasa juga ya, ngomongin pusing kerjaan).
terima
kasih telah membaca,
Love,
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar